 Arabic
Arabic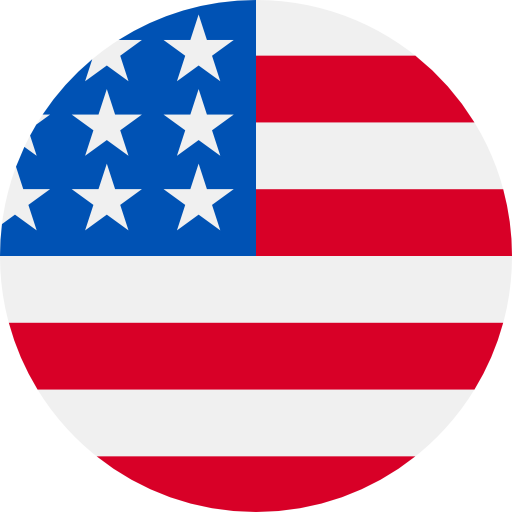 English
English Deutsch
Deutsch French
French Italian
Italian Español
Español Català
Català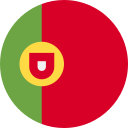 Português
Português Nederlands
Nederlands 日本語 Japanese
日本語 Japanese Polski
Polski Russian
Russian Svenska
Svenska Ukrainian
Ukrainian Türkçe
Türkçe Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia Bahasa Melayu
Bahasa Melayu ไทย Thailand
ไทย Thailand Filipino
Filipino हिन्दी Hindi
हिन्दी Hindi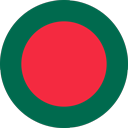 বাংলা Bengal
বাংলা Bengal اردو Urdu
اردو Urdu Tiếng Việt
Tiếng Việt 한국어 Korean
한국어 Korean 粵語 Cantonese
粵語 Cantonese 繁體字 Taiwan
繁體字 Taiwan 中文 Chinese
中文 Chinese 閩南語 Bân-lâm-gú
閩南語 Bân-lâm-gú Bulgarian
Bulgarian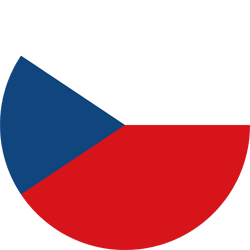 Čeština
Čeština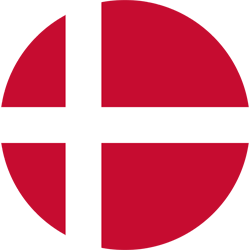 Dansk
Dansk Esperanto
Esperanto Euskara
Euskara فارسی Persian
فارسی Persian עברית Hebrew
עברית Hebrew Magyar
Magyar Norsk Bokmål
Norsk Bokmål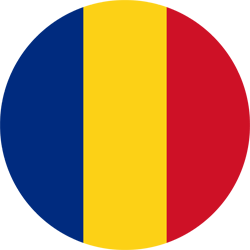 Română
Română Srpski
Srpski Srpskohrvatski
Srpskohrvatski Suomi
Suomi Asturianu
Asturianu Bosanski
Bosanski Eesti
Eesti Ελληνικά
Ελληνικά Simple English
Simple English Galego
Galego Hrvatski
Hrvatski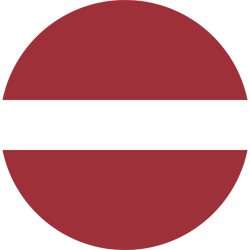 Latviešu
Latviešu Lietuvių
Lietuvių മലയാളം
മലയാളം Македонски
Македонски Norsk nynorsk
Norsk nynorsk Slovenčina
Slovenčina Slovenščina
Slovenščina Tamil
Tamil
Lilin-Lilin Kertas
LILIN-LILIN KERTAS
Firman Nofeki
MAN Padang Japang
“Apa yang akan Kau pikirkan, ketika kertas dan lilin-lilin ini menyatu?”
“Aku yakin, kertas ini akan menjadi abu dan lilin-lilin ini akan lekas mencair tanpa perlu menunggu waktu.”
Seketika tangan-tangan itu memeluk tubuh mungilku. Serentak menciumi pipi dan keningku. Kedua pipiku hangat disirami air mata mereka yang menggelegak bahagia.
Lembaran-lembaran kertas itu menggigil ditiup angin. Sesekali berhamburan menabrak dinding-dinding kayu. Perlahan alunan lagu “Happy Birthday” mengalun dalam ruangan 4x4 meter itu. "Jadilah lilin-lilin itu Anakku, yang tidak pernah habis sebesar apapun api membakarmu. Jangan Kau menjadi kertas, meskipun kecil api yang membakar, Kau akan tetap sirna sebagai abu."
Amak memandangku lekat-lekat. Kedua tangannya kini berada di kedua pipiku. Kemudian kami bertiga berangkulan dalam tawa bercampur air mata.
Ah..., tapi itu dulu kawan. Sebelum kenangan-kenangan itu sempat kubakar menjadi masa lalu.
***
Hujan baru saja reda. Tinggal sisa-sisa gerimis kecil, dan bau lembab udara menempel sebentuk bulatan kristal di kaca jendela koridor. Kulirik arloji, jam menunjukkan angka 16:30 Wib. Dua jam lebih aku terkurung hujan deras, sendirian di bangku koridor sekolah. Kuhentikan suara harmonika yang menyayat. Kutatap langit. Senja perlahan menyelimuti kota. Masih bewarna keruh, bukan keemasan. Masihkah langit menyimpan bubuk hujan, yang siap turun kapan saja. Tanpa terus berpikir,segera kukejar waktu. Jalanan terasa licin dan berlenyah. Roda sepeda ontel ini menjerit setiap kali ku percepat putarannya. Usia yang sudah seperempat abad membuat jari-jarinya mulai mengerut. Sebagian bautnya sudah longgar, bahkan ada yang lepas. Warisan dari kakek kepada abah. Dari abah diwariskan kepadaku. Kelak, jika masih panjang usianya akan kuwariskan lagi kepada anak-anak dan cucuku. Agar pewarisnya selalu dikenang sepanjang masa.
Di seberang jalan, anak-anak telah ramai pergi mengaji. Wan Nipah melambai dari jenjang surau. "Ndak ke surau Kau Ing?"
"Yo, sabanta lai."
Wan Nipah masuk ke dalam surau. Biasanya dia akan mengaji lima belas menit sebelum azan dikumandangkan. Senja begitu suram. Begitu buram. Tapi aku bisa menangkap cahaya dari mata amak,melihat anak semata wayangnya ini pulang agak terlambat.
"Mak sudah siapkan air hangat untuk mandi, lekaslah."
"Iya Mak." Aku mencium tangan amak yang berbau asap. Berarti amak baru saja dari dapur. Dari balik serambi telingaku menangkap alunan melodi khas minang dari saluang abah. Menikmati senja dengan irama saluang sambil memandangi hamparan sawah dan gunung-gunung yang berdiri megah adalah kenikmatan tersendiri bagi abah.
***
"Sudahkah Kau beri makan anjing-anjing itu Sum?"
Wanita yang acap kali dipanggil Sum itu terperanjat. Baki yang berisi piring-piring kotor di tangannya hampir jatuh, pecah berserakan. Kemudian bergegas ke belakang. Dengan wajah gugup dibawanya dua mangkok makanan anjing dan ia masukkan ke kandangnya. Mak hampir terjerembab menaiki tangga ketika anjing-anjing itu dengan kerasnya menyalak. Marah karena jatah makannya terlambat pagi ini.
Kadang, aku kasihan melihat amak yang diam-diam membekam air mata di balik kulit-kulit tuanya yang mulai keriputan. Seolah kami menjadi kambing hitam dari PHK yang dialami abah lima tahun silam. Di-PHK dari perusahan marmer milik belanda di Aceh, yang mengalami kerugian besar akibat tsunami. Seolah menjadi meriam hitam bagi abah. Acap kali meledak, menggoncang seisi rumah. Kamilah korban yang menelan abu dari ledakan amarah yang sungguh dahsyat.
Kehidupan kami berubah 180 derajat. Rumah di Aceh dijual. Rumah berukuran 6x4 meter inilah hasil dari penjualan itu. Dan dua petak sawah yang yang kini masih tergadai di tangan Wak Ramlan. Rumah yang tidak secara penuh ditutupi atap. Bila hujan deras mengguyur, kami terpaksa hidup mengendap-endap dalam semesta yang lembab. Merayap-rayap dalam gelap. Maklum listrik memang belum sempat menyentuh kampung kami. Sering terbayang dalam fikiran untuk kembali hidup berkecukupan. Sering aku mendengar sendok berdenting menyentuh piring. Decak mulut yang dipenuhi makanan dan sendawa. Berbincang-bincang sambil menonton televisi. Semua adalah hayal yang bermedan dalam frustasi.
Di rumah kayu inilah kami hidup dan bernapas. Bergerak dan beraktivitas. Pada mulanya memang terasa menyiksa. Punggung terasa pegal bangun di pagi hari, karena harus tidur di atas dipan beralaskan kayu dan jerami. Meskipun selalu kedinginan, alhamdulillah kami masih bisa makan. Meskipun kadang cuma sekali sehari. Hasil pekerjaan amak sebagai petani garapan tidaklah seberapa. Dengan kebiasaan menyisihkan segenggam beras setiap kali menanak mampu menjadi penolong ketika beras dalam buntil benar-benar telah habis.
Bila memang tidak ada yang akan dimakan, amak biasanya akan membacakan sajak untukku. Kamipun akan terlelap dalam rintihan perut menahan lapar.
Coba lihat Nak,coba lihat
Karung beras yang menganga disudut lumbung
Dan periuk kita menggelegak menanak remah harapan
Akan Kau dengar anakku, deraman-deraman nakal disisi
lambungmu
Coba lihat Nak
Bara kehilangan api
Cerobong kehilangan asap
Buntil-buntil melapuk dimakan cuaca
Tapi cukuplah anakku, keringat putihmu yang kau rasai
Dan dingin jemariku menyentuhmu hingga esok pagi
“Sudah, Wak Ramlan bilang sudah menyewa organ tunggal untuk alek anaknya nanti.”Suara abah lirih.
Matanya cekung lurus menyapa langit-langit. Diisapnya cerutu kuat-kuat. Asap-asap putih mengepul di udara. Berangsur-angsur hilang terbawa angin. Lenyap bersamaan dengan beban pikiran. Amak hanya terdiam, tidak kuasa lagi menjawab suara putus asa abah. Kepalanya terus menekur pada kain sarimin di tangannya. Sebentar-sebentar ia berhenti. Berdiri mendekati jendela. Menembus pandangan melalui kaca yang sebagian pecah dan retak. Menatap kaki gunung Sago yang menancap kuat hingga ke ulu hati. Padi-padi merunduk menahan beban. Sebuah serambi kayu di sudut rumah kini bisu. Kedinginan di tempatnya.
“Minangkabau tanpa saluang tidak bisa lagi disebut Minang. Minang akan hilang, akan tinggal kabau yang sangat sulit ditusuk hidungnya. Keras. Sama seperti hati orang-orang minang masa kini, yang tidak pernah lagi tersentuh budaya-budaya minang.”
Aku teringat percakapan dengan abah di serambi sebulan lalu. Begitu kuat budaya Minang ini mengakar ke hatinya. Lebih kuat dari akar-akar pinus yang menancap di lereng-lereng Gunung Sago.
Di-PHK dari perusahan marmer membunuh semangat hidup abah. Lebih banyak mengurung diri, seperti matahari yang kehilangan timur untuk terbit. Sejak itulah hidupku dihiasi cerita-cerita yang keluar dari bibirnya. Cerita tentang saluang sebagai budaya minang yang harus dilestarikan. Kadang kadang cerita tentang binatang buruannya yang lari ke arah rimba. Dicabik cabik sepuluh ekor anjing sekaligus.
Sering terdengar suara piring dibanting, atau gelas pecah bergeming jika perburuannya gagal. “Harusnya abah bekerja bukannya menghabiskan waktu untuk berburu yang tidak ada manfaatnya.”
“Jangan Kau menceramahiku Sum.”
Plakk.
Tempeleng itu meluncur bak roket berkekuatan 235 km per jam. Maka akan terdengar suara pintu dibanting. Tangis amak akan pecah menyapu langit.
Jati diri abah perlahan muncul semenjak bergabung dengan grup randai Haji Romlan sebagai pemain saluang. Grup ini begitu tenar di masyarakat. Tapi cuma dua tahun, sebelum organ tunggal memasuki kampung kami. Banyak grup-grup saluang dan randai mulai gulung tikar. Sekarang, di mana ada perhelatan pasti akan dihiasi dengan organ tunggal. Penduduk kampung akan membawa anak-anak mereka untuk menonton, bahkan sampai bergadang hingga larut malam. Yang mereka saksikan bukanlah musik atau nyanyiannya, tapi artis-artis berpakaian seksi yang meliuk-liuk di atas pentas. Kalaupun ada acara saluang paling yang akan menonton hanyalah bapak-bapak tua yang memang hatinya telah melekat dengan saluang. Biasanya yang masih bersedia memanggil saluang untuk helat hanyalah penduduk yang ekonomi rendah yang tidak mampu memanggil organ tunggal yang ongkos sewannya jutaan. Berbeda dengan saluang yang hanya dihargai tujuh ratus ribu dari malam sampai pagi. Hasil itupun harus dibagi dengan tujuh orang teman abah. Situasi itulah yang membuat tawa di rumah ini sering terbenam. Hanya ada murung. Dingin dan sepi. Semua dibungkus perasaan temaram.
Aku duduk menjuntai di pinggir serambi. Terlihat rambut putih abah mengkilap tertimpa cahaya senja. Perlahan abah meniup ditangannya. Irama irama semesta mengalun. Suara yang keluar begitu menyedihkan. Menyayat. Tidak menyisakan ruang kegembiraan untuk selarik senyum yang kurindukan.
"Sudahlah! Tidak usah hiraukan abah. Kalian sajalah yang makan, abah sudah kenyang."
Matanya tengadah menatap langit. Mencari arti kegelapan.
"Tapi Bah, dari tadi siang kan."
"Sudah, sudah..., abah sudah kenyang. Kau jangan membantahku sum."
Garis kekesalan mulai tampak dari ucapan abah yang memotong kata-kata amak. Amak terdiam. Ia mengerti, kalau terus mengajak abah hanya sebuah kebodohan yang akan meledakkan meriam hitam di hati abah. Hati amak bergemuruh. Hujan di matanya ingin segera turun, namun dibekamnya kuat-kuat. Amak kembali ke meja makan dengan tangis yang tertahan. Kami pun makan tanpa abah. Ada rasa iba menari-nari disetiap suapan nasi kemulutku.
Lebih dari seminggu, semenjak usahanya gagal menawari mengisi saluang pada acara alek anak Haji Ramlan abah lebih banyak mengurung diri. Hilir mudik tidak karuan. Kadang-kadang menyendiri di serambi. Pikirannya menerawang entah kemana. Ke puncak Gunung Sago yang menjulang di udara, atau pada kemuning padi yang menunggu musim panen tiba. Abah tidak pernah keluar rumah,kecuali ada teman yang mengajak pergi berburu. Begitulah, betapapun besar masalah yang dihadapi, ajakan berburu adalah angin segar yang kembali mengencangkan urat sarafnya. Kalau aku coba bertanya kenapa abah sangat suka berburu, jawabannya pendek saja, "Kalau tidak berburu kedua anjing ini akan mati kelaparan."
Apalagi kadang diperburuan itu ada diadakan semacam taruhan. Tentu bagi anjing mereka yang sanggup mematikan binatang buruan yang akan memenangkannya.
Seperti hari ini. Wak Ramlan mengajak abah berburu ke Bukit Rimbo Batu. Sebuah bukit yang dipenuhi tumbuhan pinus besar-besar. Rumputnya mencapai lutut orang dewasa, yang menutupi jurang-jurang terjal di sekelilingnya. Batu-batu besar dan terjal seringkali menjadi ranjau bagi orang-orang yang berjalan di dalamnya. Wak Ramlan berani mengganjal tiga ratus ribu kalau anjing abah mampu melumpuhkan satu ekor babi. Sepulang dari rumah Wak Ramlan kemarin wajah abah tampak lebih bahagia. Sepanjang malam hanya berburu saja ceritanya. Aku dan amak hanya bisa mengurut dada.
"Woiii..., Kandiak gadang lari ka rah rimbo!" Seorang pemburu berteriak dengan lantangnya, sambil menunjuk ke jalanan kosong di antara rentetan pinus yang menjulang tinggi di udara. Sontak anjing-anjing mereka dilepaskan. Dengan garang dan liarnya anjing-anjing itu berlari mengilas rerumputan dan ilalang. Di belakang, para pemburu dengan ligatnya mengikuti anjing-anjing mereka. Sorak mereka membahana di udara.
Abah berlari dengan kencangnya. Napasnya memburu. Tidak sabar melihat taring anjing-anjingnya menempel di kulit babi hutan yang kini sedang diburu. Ia kerahkan sisa tenaga. Keringat membasahi melunturkan debu-debu kotor di wajahnya. Kaos tipis yang ia kenakan telah menempel di badan akibat keringat yang melekat.
Tapi apa bisa dikata, kaki abah menabrak sebuah batu besar yang tidak kasat mata, karena ditutupi oleh rerumputan hijau yang tinggi. Tak ayal, tubuh abah terpelanting tepat di bibir jurang yang tidak terlihat oleh ilalang yang menutupi. Hanya teriakan abah yang terdengar oleh Wak Ramlan yang berada dua puluh meter di belakang abah. Suasana di perburuan berubah mencekam. Keringat dingin mengalir deras, seirama degup jantung yang begitu kencang. Bulu roma ikut menegang. Beberapa orang mulai mencoba turun ke dalam jurang. Kondisi jurang yang dalam membuat orang-orang kesulitan. Ditambah lagi belukar yang merambahi sekeliling jurang.
Langit temaram. Berubah mendung. Kemudian berubah rintik-rintik air. Suara gemuruh dan halilintar berpadu loncatan alam. Semakin malam hujan turun semakin tidak karuan saja. Guruh tidak henti berkelakar menggeluti kecemasan.
Semburat sinar fajar menyibak kegelapan yang menyergap alam semalaman. Wajah Wak Ramlan yang bercerita semakin menegang. Amak bersandar lesu di dekat dinding kayu. Dua tetes bening sudah acap kali ia tepis dengan kerudung putihnya. Akupun hanya mampu membisu sambil memeluk kedua lutut. Mengatur napas yang tidak lagi stabil.
Tak lama seorang pria kurus berlari dengan tubuh kotor. la berdiri di depan pintu. Ia bungkukkan tubuh sambil memegangi kedua lututnya. Ia mengatakan bahwa jasad abah tidak ditemukan tepat dimana ia jatuh. Kemungkinan terbesar yang terjadi, tubuh abah telah diterkam binatang buas, dan diseret entah kemana. Suasana dingin itu berubah erangan panjang dari amak. Begitu menyayat.
Amak pingsan selama dua hari. Namun satu hal yang tidak bisa kulupakan, kejadian itu tepat disaat usiaku menginjak 17 tahun. Sebuah kado terburuk yang mengajarkanku arti perih sebuah kehilangan.
Satu bulan jasad abah belum juga ditemukan. Entah di mana keberadaannya. Tersangkut di sebuah cabang pohon,atau jatuh kedalam sungai dan hanyut entah kemana. Atau memang telah dimangsa hewan buas dan dibawa ke sarangnya. Apakah abah masih hidup dan kini sedang barada disuatu tempat. Allahualam. Tapi yang jelas aku telah rela menerimanya. Meski sesekali masih kudengar di penghujung akhir malam isak tangis amak, yang menyajakkan bait-bait kehilangan setiap aku tidur di pangkuannya.
Coba baca Nak, coba baca
Berita ayahmu yang jatuh dari ketinggian
Di sebuah akhir malam
Tutup telingamu, dikalau
Dentuman keras itu membuat napasmu sesak
Dan darahmu deras menggelegak
Agar malam ini, anakku
Amak melihatmu telentang tanpa nyanyian abah
Dan tanpa decitan periuk
Pertanda nasimu masak diperapian
Lalu kami akan sama-sama menangis dalam kesunyian. Kini saluang bambu itu merenung sendiri kehilangan majikannya. Mulai melapuk dimakan cuaca.
Masih terdiam. Kupandangi tumpukan-tumpukan kertas berdebu di atas sebuah meja kayu. Entah apa penyebabnya berdebu. Debu-debu dari jalanankah? Atau akibat telah lama tersentuh waktu.
Debu kusapu dengan tangan. Di setiap lembar terdapat coretan-coretan yang sudah tampak kusam. Sesekali kuberdiri ke arah jendela kayu. Menembus pandang pada kabut yang menyekap penglihatan. Menatap serambi yang bisu, kedinginan di tempatnya.
Mulai kubaca kertas itu lembar demi lembar, berteman lilin yang menyadap kegelapan. Air mataku meleleh disebuah kertas yang sudah hampir sobek. Kubaca lagi tulisan itu dalam-dalam.
"Jadilah lilin-lilin itu, anakku! Yang tidak pernah habis sebesar apapun api membakarmu. Jangan kau menjadi kertas! Meskipun kecil api yang membakar, Kau akan tetap sirna sebagai abu."
Sekarang aku benar-benar mengerti apa yang akan terjadi ketika kertas dan lilin itu menyatu. Sebelum kenangan itu benar-benar kubakar menjadi masa lalu.